

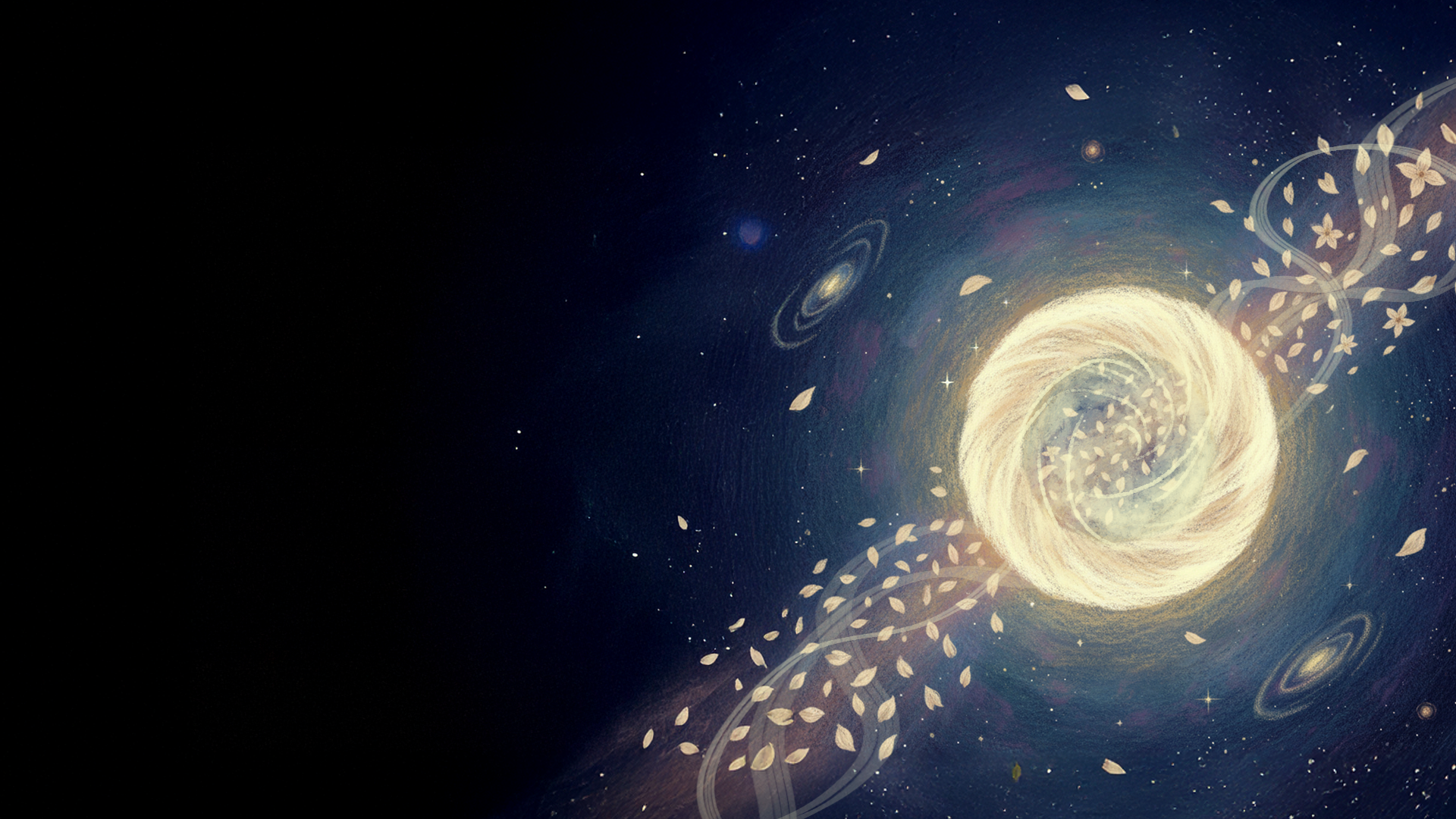
Di cerita kali ini, barangkali banyak di antara kalian yang pernah merasakannya. Kisah dua remaja di masa muda, tentang cinta yang penuh gairah, dan aroma seringkali menjadi kambing hitam di saat harapan untuk berbahagia bersama tidak tercapai, melainkan perpisahan menjadi akhirnya.
Kami tidak akan banyak mengantarkan prolog panjang, kami akan segera mengajak kamu memasuki lorong waktu seorang perempuan bernama Zara—katanya, panggilan kecil ini juga sudah disesuaikan dengan cara seseorang memanggilnya yang sempat keranjingan aroma vanilla.
Dan kita akan telusuri bagaimana Zara menghadapi aroma yang menjadi penyimpan banyak momen membahagiakan, tapi juga luka yang tidak kunjung sembuh dalam waktu lama.
Kalau aku dengar kata wangi, aku jadi keinget momen di suatu malam yang sebenarnya sederhana dan biasa-biasa saja. Mataku setengah mengantuk duduk di bangku motor menjadi penumpang.
Kami berdua tidak mengenakan helm karena jarak tempuh kami yang dekat dan di jalan kecil pedesaan. Rambutnya bergemerisik dan renyah, bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri seperti seikat bayam di tukang sayur.
Segar, hidup, dan entah kenapa selalu membuatku betah melihatnya. Dalam momen itu, rambut orang di depanku sangat wangi, seperti baru selesai mandi.
Dia-kupanggil si Rambut Bayam-punya ciri khas unik. Orang ini mengeluarkan bau vanilla. Entah dari parfum, sabun, dan shampo yang dipakainya.
Kalau aku dengar kata wangi, aku jadi keinget momen di suatu malam yang sebenarnya sederhana dan biasa-biasa saja. Mataku setengah mengantuk duduk di bangku motor menjadi penumpang.
Kami berdua tidak mengenakan helm karena jarak tempuh kami yang dekat dan di jalan kecil pedesaan. Rambutnya bergemerisik dan renyah, bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri seperti seikat bayam di tukang sayur.
Segar, hidup, dan entah kenapa selalu membuatku betah melihatnya. Dalam momen itu, rambut orang di depanku sangat wangi, seperti baru selesai mandi.
Dia-kupanggil si Rambut Bayam-punya ciri khas unik. Orang ini mengeluarkan bau vanilla. Entah dari parfum, sabun, dan shampo yang dipakainya.

Di semester antara, ketika hari-hariku penuh tekanan, aku merasa sepi meskipun ramai. Rasanya tidak ada ruang untuk sendiri, dua puluh empat jamku didominasi untuk kegiatan rapat, survey lapangan, membuat laporan, dan eksekusi program kerja. Hidupku seperti kehabisan energi.
Aku sering pulang dengan mata berat, tubuh lelah, dan perasaan kosong. Dalam riuh jadwal itu, aku bahkan lupa bagaimana rasanya duduk membaca buku di taman atau sekadar menonton senja tenggelam.
Pada saat itu, rasanya aku tidak punya siapa-siapa di pihakku. Bahkan, berulang kali aku mengajak temanku bertemu, mereka selalu tidak bisa meluangkan waktunya. Ya, bagaimana pun pada saat itu, sepertinya kondisi semua orang ada dalam fase yang sama, apalagi teman seangkatanku.
Berulang kali kuperingatkan pada diri sendiri dan menarik batas serta jarak. Tapi, memang begitu nyatanya. Aku kehilangan ruang untuk diriku sendiri. Aku bahkan tidak dapat mendengar gemuruh jantungku sendiri.

Di semester antara, ketika hari-hariku penuh tekanan, aku merasa sepi meskipun ramai. Rasanya tidak ada ruang untuk sendiri, dua puluh empat jamku didominasi untuk kegiatan rapat, survey lapangan, membuat laporan, dan eksekusi program kerja. Hidupku seperti kehabisan energi.
Aku sering pulang dengan mata berat, tubuh lelah, dan perasaan kosong. Dalam riuh jadwal itu, aku bahkan lupa bagaimana rasanya duduk membaca buku di taman atau sekadar menonton senja tenggelam.
Pada saat itu, rasanya aku tidak punya siapa-siapa di pihakku. Bahkan, berulang kali aku mengajak temanku bertemu, mereka selalu tidak bisa meluangkan waktunya. Ya, bagaimana pun pada saat itu, sepertinya kondisi semua orang ada dalam fase yang sama, apalagi teman seangkatanku.
Berulang kali kuperingatkan pada diri sendiri dan menarik batas serta jarak. Tapi, memang begitu nyatanya. Aku kehilangan ruang untuk diriku sendiri. Aku bahkan tidak dapat mendengar gemuruh jantungku sendiri.
Lalu, dia datang, si Rambut Bayam.
Lalu, dia datang, si Rambut Bayam.
Tidak dengan kejutan besar, hanya dengan cara sederhana, memahamiku dan mengulurkan tangannya untukku. Dia tiba-tiba menjadi orang pertama yang tidak membiarkanku terjatuh. Menyuruhku berhenti sejenak dan mengingatkanku tentang hidup layaknya kereta yang tidak datang karena lebih cepat, tapi datang sesuai jadwal dan waktu yang tepat.
Sejak dia datang, dia selalu mau mengantarku ke mana saja. Ada di satu waktu, dia menjemputku dari tempat les, sepertinya dia melihat raut wajahku yang sudah pucat, suntuk, dan kelelahan.
Aku juga tidak begitu banyak berbicara, hanya naik motor, dan hening hingga depan rumah. Pas tepat ada di depan rumah, aku berpamitan, tapi ia tiba-tiba mengeluarkan vitamin dari dalam tasnya, lalu memberikannya kepadaku. Dia tidak banyak berbicara, hanya memberikannya kepadaku dengan sedikit kata saja,
“Nih, aku pamit dulu, ya” Lalu dia pergi. Aku bahkan belum sempat berterima kasih.
Tidak dengan kejutan besar, hanya dengan cara sederhana, memahamiku dan mengulurkan tangannya untukku. Dia tiba-tiba menjadi orang pertama yang tidak membiarkanku terjatuh.
Menyuruhku berhenti sejenak dan mengingatkanku tentang hidup layaknya kereta yang tidak datang karena lebih cepat, tapi datang sesuai jadwal dan waktu yang tepat.
Sejak dia datang, dia selalu mau mengantarku ke mana saja. Ada di satu waktu, dia menjemputku dari tempat les, sepertinya dia melihat raut wajahku yang sudah pucat, suntuk, dan kelelahan.
Aku juga tidak begitu banyak berbicara, hanya naik motor, dan hening hingga depan rumah. Pas tepat ada di depan rumah, aku berpamitan, tapi ia tiba-tiba mengeluarkan vitamin dari dalam tasnya, lalu memberikannya kepadaku. Dia tidak banyak berbicara, hanya memberikannya kepadaku dengan sedikit kata saja,
“Nih, aku pamit dulu, ya” Lalu dia pergi. Aku bahkan belum sempat berterima kasih.
Ada satu ketika kami sedang ikut kegiatan yang sama dari kampus, saat itu kegiatan sedang padat-padatnya dan aku yang ceroboh sering terjatuh hingga kehilangan sandal, sampai akhirnya bertelanjang kaki.
Entah dari mana, ia tiba-tiba menghampiri, tanpa bicara satu katapun, ia memosisikan sandal jepitnya agar sejajar dengan kakiku. Lalu, ia pergi begitu saja.
Ketika aku sakit dan tidak mampu menghadiri acara pensi bersama kawan-kawan lainnya, ia membawaku berputar-putar dengan motornya, seakan bilang, “agar kamu juga bisa merasakan suasana pesta meski dari kejauhan, agar kamu ingat bahwa kamu tetap harus bersenang-senang.” Ia sangat minim bicara, tetapi tindakannya betul-betul menjaga.
Aku yang selalu ingin mandiri tiba-tiba belajar menerima bahwa ada kalanya kita butuh ditolong, tanpa kita meminta. Dan meski tidak pernah kuakui dengan jelas, caranya memperlakukanku membuat jantungku bergetar.
Bentuk act of service dari perihal kecil hingga besar membuatku merasa dilihat, benar-benar dilihat, yang bahkan diriku pun sering kali tidak menyadarinya.
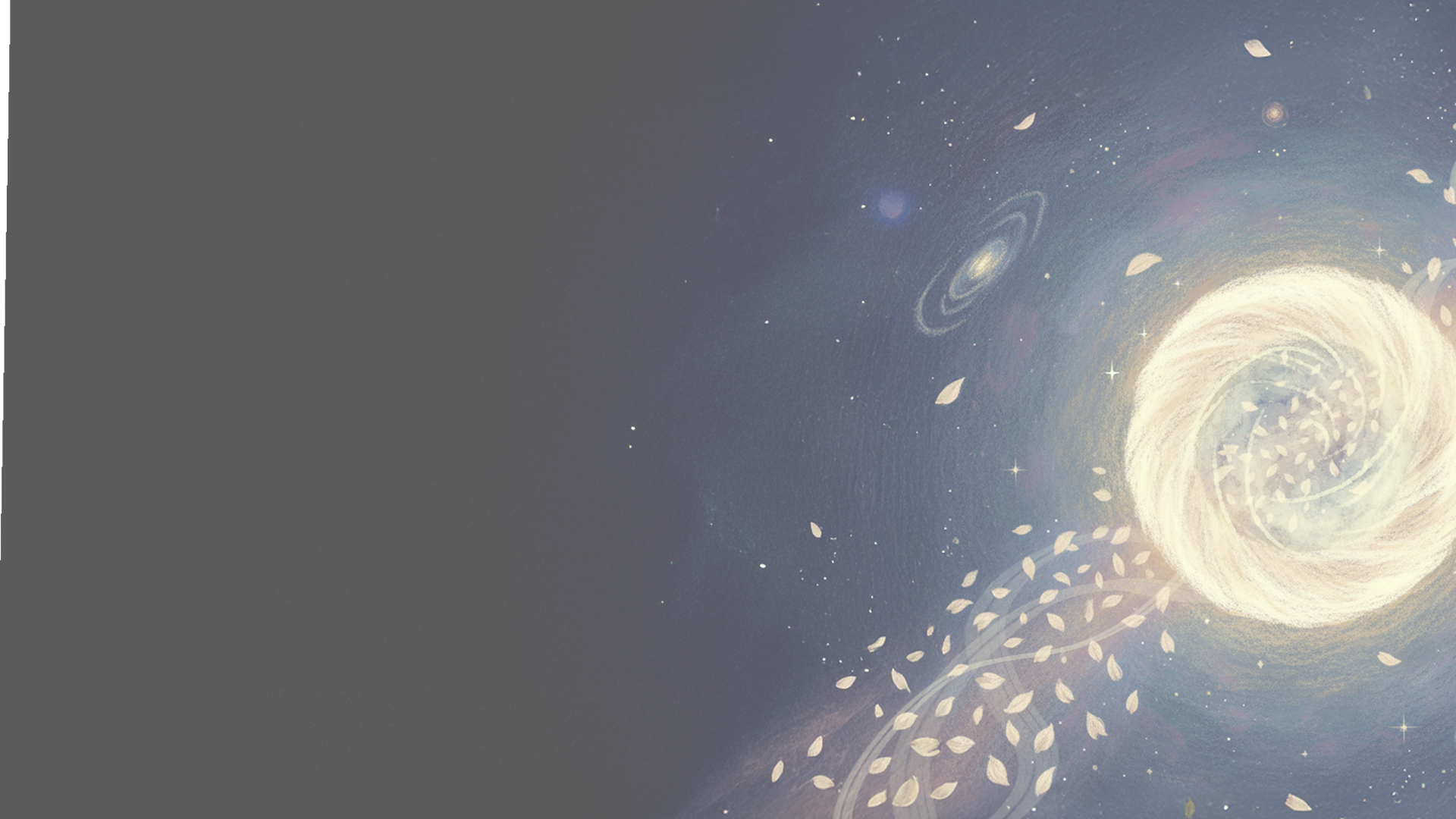
Tapi seperti semua bahasa, ada saatnya ia terdistorsi ...
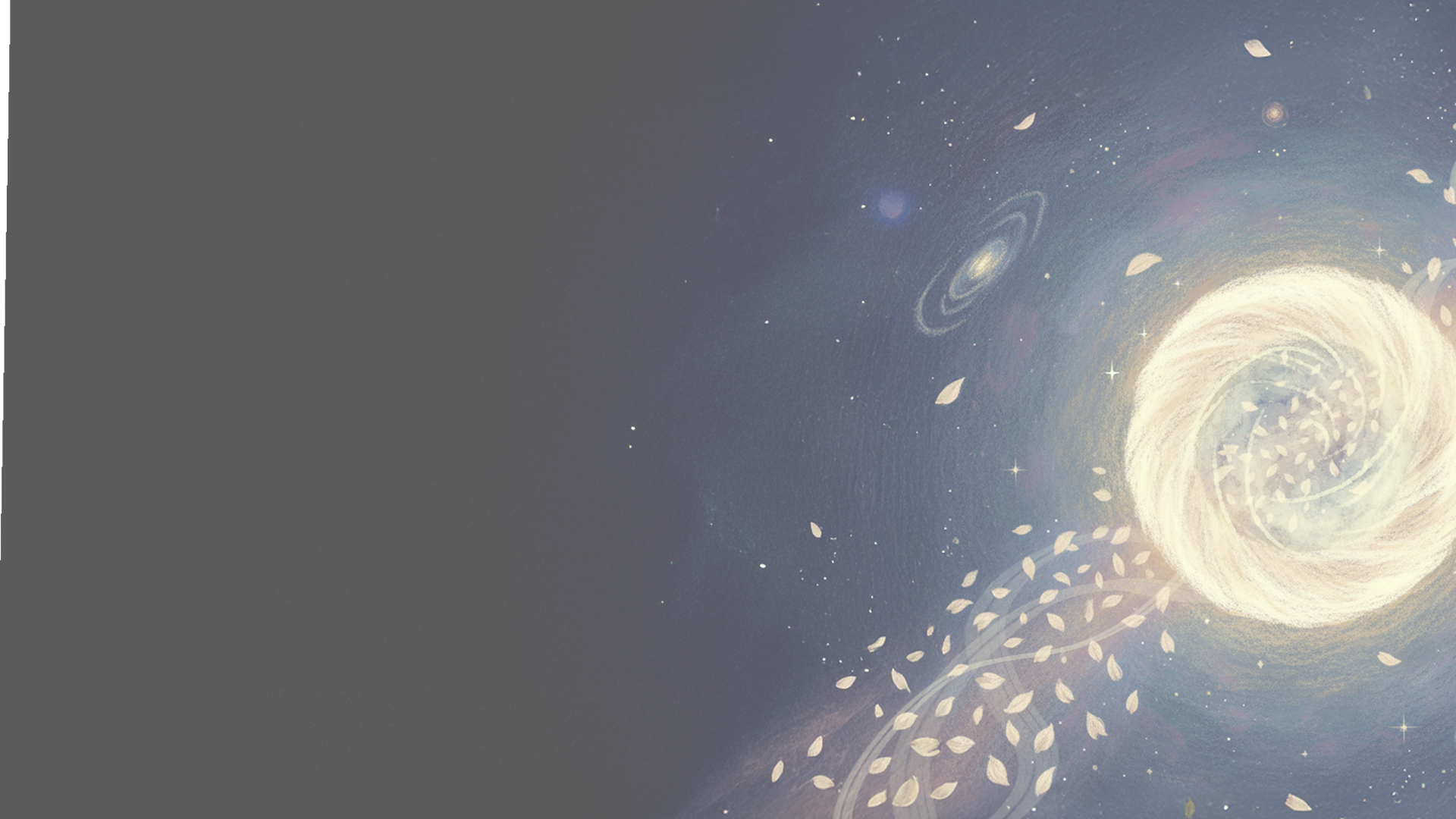
Tapi seperti semua bahasa, ada saatnya ia terdistorsi ...
Ada masa-masa ketika dia tidak melihatku sama sekali, tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia sering sibuk dengan rencana-rencana yang besar, dengan mimpi yang ia kejar seolah dunia ini hanya miliknya. Dan di situ, aku merasa mengecil.
“Apakah aku benar-benar cukup untuknya?” pertanyaan itu selalu berisik di kepalaku. Tapi, di waktu yang sama aku pun mulai menjaga jarak darinya, sebagai bentuk, aku ingin menyelamatkan diriku dari luka. Alih-alih menjaga diri dari luka, justru aku menyesal akan keputusan bodoh ini.
Jawaban akhirnya datang, dengan cara yang paling menyeksakkan, “kamu akan lama ya bekerja di sana?” kataku saat kita bertemu di satu cafe “dua tahun” “...” "sesuai perkataanmu dulu, kita ga boleh lebih jauh lagi. Jadi, aku bakal pergi jauh sampe kamu ga bisa menjangkaku lagi ..." kalimat yang dia ucapkan lebih banyak dari biasanya. Menurutku, ini bukan kalimat berpami- tan, tapi pergi meninggalkan. Lalu, tahu-tahu ia sudah berada di lain benua.
Ada masa-masa ketika dia tidak melihatku sama sekali, tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia sering sibuk dengan rencana-rencana yang besar, dengan mimpi yang ia kejar seolah dunia ini hanya miliknya. Dan di situ, aku merasa mengecil.
“Apakah aku benar-benar cukup untuknya?” pertanyaan itu selalu berisik di kepalaku. Tapi, di waktu yang sama aku pun mulai menjaga jarak darinya, sebagai bentuk, aku ingin menyelamatkan diriku dari luka. Alih-alih menjaga diri dari luka, justru aku menyesal akan keputusan bodoh ini.
Jawaban akhirnya datang, dengan cara yang paling menyeksakkan, “kamu akan lama ya bekerja di sana?” kataku saat kita bertemu di satu cafe “dua tahun”
“...”
"sesuai perkataanmu dulu, kita ga boleh lebih jauh lagi. Jadi, aku bakal pergi jauh sampe kamu ga bisa menjangkaku lagi ..." kalimat yang dia ucapkan lebih banyak dari biasanya. Menurutku, ini bukan kalimat berpami- tan, tapi pergi meninggalkan. Lalu, tahu-tahu ia sudah berada di lain benua.
Aku terdiam. Rasanya seperti ditikam dengan pisau yang dilapisi madu, manis karena aku bangga padanya, tapi perih karena aku tidak sadar, kalau aku tidak akan pernah dilibatkan dalam proses menuju masa depannya.
Dia pergi, meninggalkanku hanya dengan sisa aroma vanilla yang menempel di jaketnya. Bertahun-tahun setelahnya, vanilla menjadi pisau bermata dua bagiku. Kadang ia manis, kadang ia menghantui.
Ada hari ketika ia terasa seperti cahaya lilin, hangat, menenangkan. Tapi ada juga hari ketika ia menjelma bayangan gelap di sudut ruangan, mengingatkanku betapa sendirinya aku sekarang.
Aku terdiam. Rasanya seperti ditikam dengan pisau yang dilapisi madu, manis karena aku bangga padanya, tapi perih karena aku tidak sadar, kalau aku tidak akan pernah dilibatkan dalam proses menuju masa depannya.
Dia pergi, meninggalkanku hanya dengan sisa aroma vanilla yang menempel di jaketnya. Bertahun-tahun setelahnya, vanilla menjadi pisau bermata dua bagiku. Kadang ia manis, kadang ia menghantui.
Ada hari ketika ia terasa seperti cahaya lilin, hangat, menenangkan. Tapi ada juga hari ketika ia menjelma bayangan gelap di sudut ruangan, mengingatkanku betapa sendirinya aku sekarang.
Aku melewati berbagai tahap kehilangan. Sejak hari itu, aku memutuskan untuk merelakannya. Di malam itu juga tangisan pertama datang dengan tubuh yang bergetar, air mata jatuh tanpa bisa dihentikan, menetes ke bantal hingga basah, seolah ingin melarutkan semua kenangan bersamanya.
Luka itu, terus berlarut selama satu bulan pertama. Awalnya, aku kira akan berakhir di sini, tapi justru semakin berlanjut ke bulan-bulan berikutnya.
Menuju bulan kedua, rindu tidak juga mereda. Berkali-kali aku berusaha menghubungi dan memperbaiki hubungan dengannya walau hanya sebatas pertemanan.
Tetapi ia sudah membangun dinding. Yang semula hangat menjadi dingin luar biasa. Seo- lah-olah memang segala perkataannya adalah upaya balas dendam karena aku pernah menarik diri darinya juga.
Lalu, masuk bulan-bulan berikutnya, tangis berubah menjadi marah. Aku marah dan melempar gelas kosong ke dinding, berteriak pada udara yang bisu, seakan dunia harus ikut merasakan hancurnya dadaku.
Setelah itu, penolakan menjelma menjadi kebiasaan, menolak membuka kotak berisi barang-barangnya, menutup hidung tiap kali aroma vanilla menyelinap, bahkan menyingkirkan parfum yang dulu pernah menjadi aroma kesukaan kami berdua.
Namun pada akhirnya, aku semakin tersiksa dan mulai sadar bahwa aku harus mencoba menerima.
Tepat satu tahun setelahnya, aku lebih banyak diam dan menatap langit malam. Ketika pagi tiba, aku bangun dengan berpeluh setelah masih memimpikannya bahkan hingga beberapa tahun kemudian.
Aku sempat menghirup aroma vanilla itu sekali lagi, tanpa berusaha mengusirnya, sambil membiarkannya menjadi bagian dari cerita yang pernah ada.
Dan aku menyadari satu hal, aroma ini tidak pernah ikut pergi bersamanya. Justru, ia bertahan di sini, menempel di udara, seperti hantu yang tidak mau diusir. Butuh waktu lama bagiku untuk berdamai.
Tapi, jika saja ada proses percepatan untuk berdamai, aku benar-benar ingin mewujudkan keinginanku, yaitu melepas aroma ini. Tapi, aku juga belum benar-benar yakin, karena, barangkali, fase denial-ku kini kambuh.
Dan saat kambuh, aroma ini berubah menjadi monster menakutkan bagi pikiranku, dan menyadarkan jika kini tinggal aku dan orang-orang. Sementara dia, sudah pergi jauh sekali.
Dan aku menyadari satu hal, aroma ini tidak pernah ikut pergi bersamanya. Justru, ia bertahan di sini, menempel di udara, seperti hantu yang tidak mau diusir. Butuh waktu lama bagiku untuk berdamai.
Tapi, jika saja ada proses percepatan untuk berdamai, aku benar-benar ingin mewujudkan keinginanku, yaitu melepas aroma ini. Tapi, aku juga belum benar-benar yakin, karena, barangkali, fase denial-ku kini kambuh.
Dan saat kambuh, aroma ini berubah menjadi monster menakutkan bagi pikiranku, dan menyadarkan jika kini tinggal aku dan orang-orang. Sementara dia, sudah pergi jauh sekali.

Cerita ini kami dapatkan dari balik store yang ada di Jogja. Saat itu, Zara adalah salah satu pelanggan kami yang datang untuk mencari aroma vanilla. Kami sempat bertanya beberapa alasan mengapa dia begitu antusias menemukan aroma vanilla dari berbagai macam varian.
Sambil mencoba satu per satu aroma yang sudah kami sajikan, itulah cerita yang kami dapat. Tentang Zara dan perasaannya yang belum benar-benar tuntas. Tapi dari raut wajahnya, tidak sedikitpun nampak luka. Tapi ceritanya, membuat kami sadar bahwa ada banyak penderitaan yang dia pendam dalam waktu lama. Dan semoga, proses berdamai dengan aroma ini bisa segera berhasil.
Dan lagi-lagi, aroma seringkali dijadikan tempat untuk bersemayamnya cinta, luka, dan rindu yang tidak terselesaikan. Setiap aroma memang punya ceritanya sendiri. Ada yang getir, ada yang manis, dan ada yang menyisakan keduanya.
Lalu, dari store yang sama, ada pula kisah lain, tentang seorang pelanggan yang kami sebut “Mas-Mas Jawa”. Bedanya, ia menyimpan kenangan first date yang sangat buruk karena dia memakai parfum beraroma kue yang sangat berlebihan. Lantas, bagaimana cinta mereka berakhir? Apakah mereka tetap kembali atau justru berakhir tidak bersama?
Bersambung ...